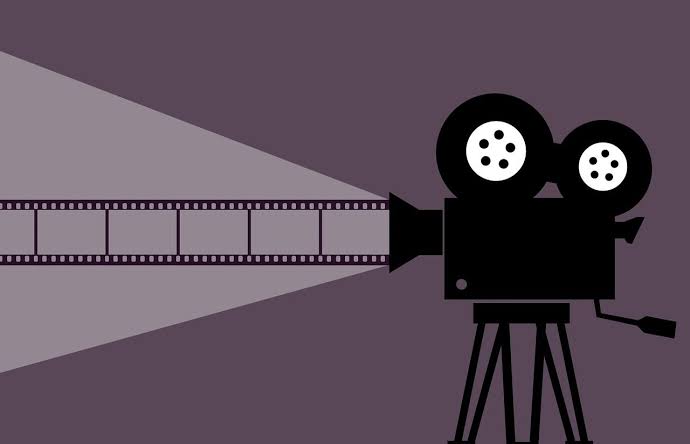***
Putraindonews.com – Jakarta | Perkembangan pesat industri film tanah air rupanya dibayar mahal oleh para pekerja film yang menjalani kondisi kerja berbahaya, penuh kerentanan, dan minim perlindungan terhadap hak mereka.
Hal ini terungkap dalam kertas posisi berjudul “Sepakat di 14: Advokasi Pembatasan Waktu Kerja dan Perlindungan Hak Pekerja Film Indonesia”
yang dirilis Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) dan Indonesian Cinematographers
Society (ICS) untuk menyambut Hari Film Nasional yang diperingati setiap 30 Maret.
Dalam kertas posisi itu, SINDIKASI dan ICS menemukan tiga masalah yang dialami pekerja film baik jenis film cerita panjang maupun iklan selama setidaknya dua dekade terakhir.
Hasil survei terhadap pekerja film yang dilakukan ICS dan SINDIKASI menunjukkan 54,11% dari total 401 responden mengaku bekerja selama 16-20 jam per hari syuting. Adapun 7,23% responden lain mengaku bekerja di atas 20 jam per hari syuting.
Kondisi kerja berkepanjangan (overwork) terjadi selama bertahun-tahun pada produksi film cerita panjang dan iklan.
“Pembiaran terhadap kondisi overwork ini sama saja seperti membunuh pelan-pelan para pekerja film atas nama passion, produktivitas, atau ilusi lainnya. Apalagi riset World Health Organization (WHO) dan International Labour Organization (ILO) telah membunyikan alarm peringatan keras akan adanya risiko tinggi pekerja meninggal akibat penyakit jantung dan
stroke apabila menjalani kerja di atas 55 jam tiap pekan,” ungkap penulis kertas posisi Sepakat di 14, Ikhsan Raharjo dalam diskusi virtual Selasa (29/3).
Dia menambahkan pekerja film juga rentan mengalami pelanggaran hak normatif. Kasus pemberi kerja ingkar janji terkait pembayaran upah sering terjadi namun tidak terdokumentasi dan tidak terlaporkan.
“Mereka sering mengalami keterlambatan pembayaran upah, upah kurang dari yang dijanjikan, dan bahkan kasus upah yang tidak dibayarkan sama sekali.” Kondisi ini diperparah dengan adanya konflik horizontal antara pekerja yang sering banting harga upah demi mendapatkan pekerjaan.
Dari data kuantitatif dan kualitatif yang terkumpul, SINDIKASI dan ICS juga menyimpulkan bahwa pekerja film Indonesia terperosok ke dalam flexploitation atau kondisi eksploitasi yang secara spesifik dirasakan oleh pekerja dalam hubungan kerja fleksibel.
“Flexploitation ditandai kondisi kerja berbahaya, tanpa kepastian dan perjanjian kerja, pengelabuan hubungan kerja, hingga absennya jaminan sosial. Kami menemukan gejala ini pada pekerja film Indonesia,” tambah Ikhsan.
Kondisi ini dipersulit dengan adanya normalisasi terhadap kondisi kerja buruk. “Ada persepsi yang menganggap kondisi kerja buruk merupakan pengorbanan yang harus dilewati pekerja muda jika ingin berkarier di industri film.”
Kertas posisi ini mengungkapkan lima faktor penyebab terjadinya masalah di atas ;
– Pertama, adanya pengabaian hukum ketenagakerjaan di sektor film yang berlangsung secara sistemik selama bertahun-tahun.
– Kedua, lemahnya posisi tawar kolektif pekerja film yang membuat mereka cenderung memperjuangkan hak normatifnya secara individual.
– Ketiga, kontrak kerja yang bermasalah dan merugikan pekerja film karena belum menjamin pemenuhan hak normatif seperti perlindungan upah, kompensasi lembur, dan jaminan sosial.
Berkebalikan dengan produksi film cerita panjang, penggunaan kontrak kerja tertulis pada produksi iklan ternyata merupakan barang langka mengingat hanya 8,22% responden yang mengaku selalu memiliki kontrak kerja tertulis.
Dengan begitu, pekerja menjadi semakin rentan terlanggar haknya karena tak memiliki kontrak kerja tertulis.
– Keempat, pemerintah belum melindungi pekerja film karena cenderung menempatkan kepentingan pekerja pada posisi yang terpinggirkan.
Perhatian tiga kementerian yang mengurus perfilman yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, cenderung lebih berat terhadap pengusaha perfilman ketimbang pekerjanya.
– Kelima, perubahan model bisnis dan teknologi yang berdampak pada kondisi para pekerja film. “Pekerja film yang memiliki pengalaman di atas 20 tahun merasakan adanya perubahan kultur kerja produksi iklan yang semakin serba kilat dan anggaran yang semakin ketat.
Overwork tak terhindarkan karena mereka harus selesaikan beban pekerjaan yang sama tapi dalam waktu yang lebih pendek,” ungkap Ikhsan.
Perlu ada sebuah gerakan bersama yang terkoordinir, komprehensif, dan melibatkan semua unsur di ekosistem film untuk mengatasi hal kompleks ini.
SINDIKASI dan ICS mendorong seluruh pihak agar menyepakati adanya pembatasan waktu kerja yang sesuai hukum ketenagakerjaan pada tahap praproduksi, produksi, dan pascaproduksi.
ICS mengusulkan 14 jam waktu syuting maksimal dengan rincian 8 jam kerja, 4 jam lembur, dan 2 jam istirahat.
Selain itu, perlu ada waktu jeda atau turnaround time selama 10 jam yang memisahkan antara akhir waktu syuting dengan awal syuting pada hari berikutnya untuk memastikan adanya cukup waktu istirahat bagi pekerja film.
“Kami menyadari bahwa isu ini bukanlah hal baru, tetapi isu yang terhitung klasik tercatat sejak 1980-an hal ini telah menjadi perhatian dari para sineas generasi terdahulu.
Terkait dengan tujuan didirikannya asosiasi ini yakni untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dengan perlindungan asuransi kerja dan kesehatan, maka kami pun merasa perkara
jam kerja amat erat mempengaruhi aspek ini.
Kami merasa ada langkah mutlak yang perlu dilakukan,” ungkap Presiden ICS, Anggi Frisca. Anggi berharap usulan ini dapat memantik ruang diskusi yang produktif dan kolaboratif untuk menyelesaikan permasalahan.
Di saat bersamaan, SINDIKASI dan ICS juga mendorong adanya penyatuan kekuatan kolektif pekerja film agar lebih kuat dalam memperjuangkan perbaikan kondisi kerja.
Asosiasi profesi film dan serikat pekerja dapat berjalan bersama dan saling melengkapi guna meningkatkan posisi tawar pekerja film di hadapan negara dan pemberi kerja. “Upaya korektif itu membutuhkan usaha kolektif yang masif untuk terwujud,” kata Ketua SINDIKASI Nur Aini.
Selain itu, jaminan terhadap pemenuhan hak para pekerja film dapat diperjuangkan melalui perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat antara asosiasi pengusaha film dan serikat pekerja. “Dengan adanya aturan main bersama, maka pekerja bisa terhindar dari pasal-pasal merugikan yang mereka sering temui di kontrak kerja perseorangan,” lanjut dia.
Di samping hak normatif, PKB juga dapat mencakup kesepakatan terhadap mekanisme
kerja ideal yang bisa menjadi acuan tiap produksi film.
Terakhir, pemerintah harus lebih aktif dalam melindungi dan menjamin kepentingan pekerja film. Ketiga kementerian harus saling bekerja sama untuk memerangi overwork dan meningkatkan perlindungan terhadap hak pekerja film. Kondisi kerja yang buruk bukan saja merugikan pekerja tapi pada akhirnya berdampak buruk pada industri film. Red/Ben
***